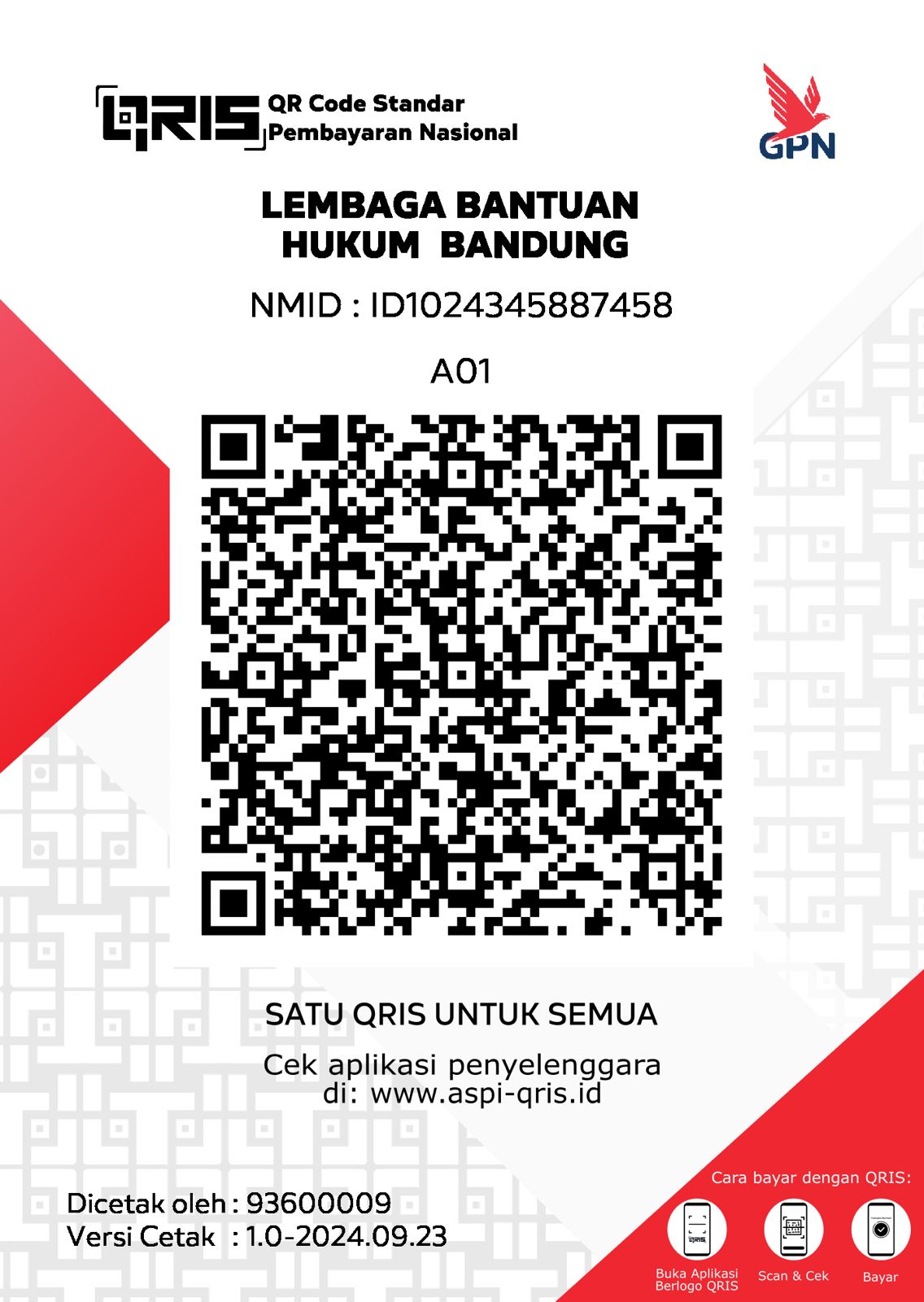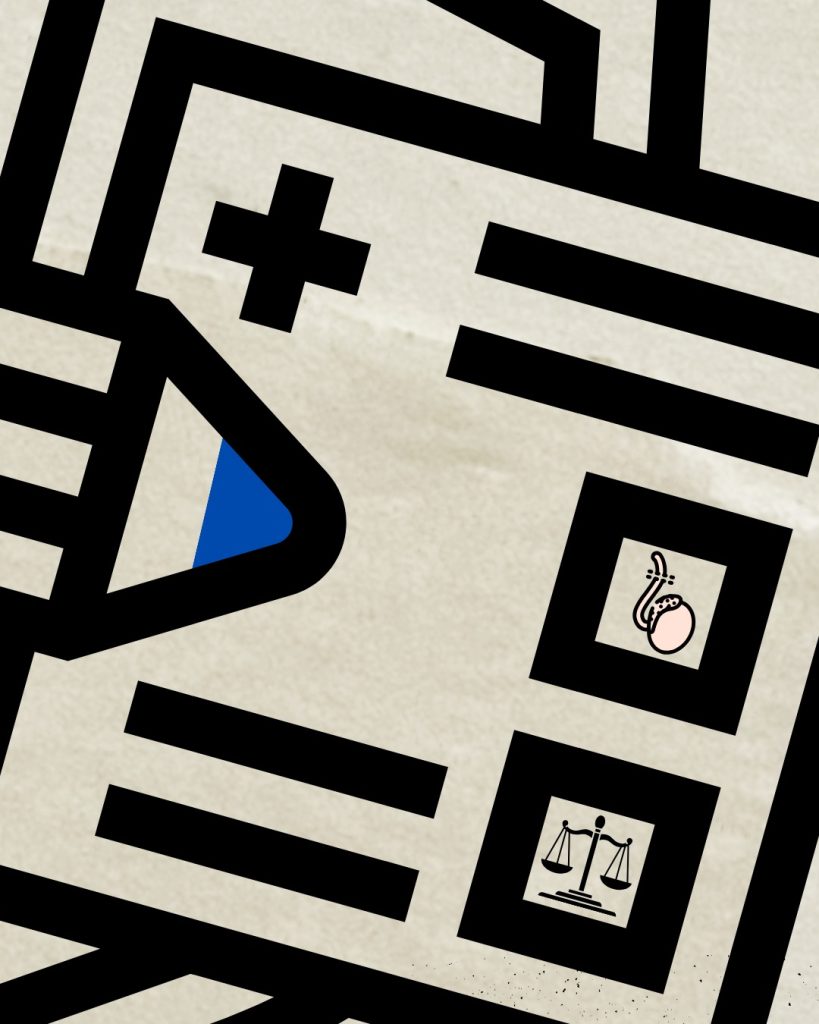
Vasektomi dan Kontrol Populasi: Antara Kebijakan dan Keadilan Sosial
Oleh: Ahmad Budi Santoso
Wacana pengendalian populasi melalui program vasektomi kembali mengemuka, kali ini dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam pernyataannya, ia mengusulkan agar vasektomi dijadikan salah satu strategi untuk menekan angka kemiskinan di kalangan masyarakat kelas bawah. Gagasan ini segera memantik kontroversi. Bukan karena metode vasektomi itu sendiri, melainkan karena sasaran dan pendekatannya yang menyasar masyarakat miskin, tanpa menyentuh akar persoalan struktural yang membuat mereka tetap berada dalam lingkaran kemiskinan.
Vasektomi adalah metode kontrasepsi permanen bagi pria yang sah dan legal. Dalam konteks hak reproduksi, seseorang tentu berhak memilih apakah ingin memiliki anak atau tidak, dan metode apa yang akan digunakan. Namun, ketika pemerintah secara aktif mendorong vasektomi kepada kelompok tertentu (khususnya masyarakat miskin) pertanyaan besar muncul: apakah ini benar-benar pilihan bebas, atau tekanan yang dibungkus sebagai kebijakan publik?
Mengontrol jumlah kelahiran di kalangan kelas bawah atas nama “penanggulangan kemiskinan” adalah pendekatan yang sempit dan tidak manusiawi. Seolah-olah kemiskinan terjadi karena orang miskin terlalu banyak memiliki anak, bukan karena negara gagal memenuhi hak dasar mereka. Narasi ini menempatkan rakyat kecil sebagai penyebab masalah, bukan korban dari sistem yang timpang. Padahal, penyebab kemiskinan jauh lebih kompleks dan menyangkut aspek pendidikan, akses kesehatan, kesempatan kerja, dan distribusi ekonomi yang tidak merata.
Alih-alih mendorong sterilitas, bukankah seharusnya negara hadir memberikan peluang bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memiliki masa depan yang lebih baik? Pendidikan gratis dan berkualitas, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta jaminan sosial adalah hak dasar yang harus diberikan negara. Ketika hak-hak ini terpenuhi, keluarga miskin punya peluang nyata untuk keluar dari kemiskinan—bukan dengan dicegah memiliki anak, melainkan dengan memastikan anak-anak mereka tidak mewarisi nasib yang sama.
Anak dari keluarga miskin bukan beban, melainkan potensi. Diberikan akses dan kesempatan yang setara, mereka bisa menjadi dokter, guru, ilmuwan, atau pemimpin masa depan. Tetapi semua itu tak mungkin terwujud jika negara justru memotong harapan itu sejak awal, lewat kebijakan yang membatasi kehidupan sebelum ia dimulai. Menyederhanakan kemiskinan menjadi masalah jumlah anak adalah bentuk pengabaian terhadap potensi kemanusiaan.
Kebijakan semacam ini juga menyimpan bahaya laten: melanggengkan stigma terhadap rakyat miskin. Mereka tidak lagi dilihat sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan dan pemberdayaan, melainkan sekadar objek kebijakan demografis. Jika tidak hati-hati, pendekatan ini dapat menjurus pada praktik diskriminatif yang menargetkan kelompok tertentu untuk dikendalikan secara biologis atas nama pembangunan.
Tentu, pengendalian penduduk pernah menjadi isu penting dalam sejarah pembangunan Indonesia, terutama pada masa Orde Baru. Namun pendekatannya pun sekarang telah banyak dikritik karena menekankan kuantitas tanpa memperhatikan kualitas hidup. Kini, saat negara semakin sadar akan pentingnya hak asasi dan keadilan sosial, pendekatan lama semestinya tidak dihidupkan kembali dengan wajah baru yang lebih rapi namun tetap menindas.
Kebijakan populasi seharusnya lahir dari dialog terbuka, edukasi yang memadai, dan penghormatan pada pilihan individu, bukan dari tekanan terselubung kepada mereka yang secara sosial dan ekonomi tidak berdaya. Tanpa kesadaran ini, program seperti vasektomi massal bisa menjadi bentuk kekerasan simbolik dan nyata terhadap kelompok yang paling rentan. Kebijakan publik harus bersandar pada prinsip keadilan, bukan sekadar efisiensi statistik.
Jika pemerintah benar-benar ingin menekan angka kemiskinan, maka cara yang paling bermartabat adalah dengan memenuhi hak dasar warga negara. Bangun sekolah di pelosok, perbaiki gizi balita, buka lapangan kerja yang layak, dan pastikan akses layanan kesehatan menjangkau hingga ke desa-desa. Itulah cara yang adil untuk mengangkat derajat rakyat kecil, bukan dengan memutus rantai keturunan mereka, tetapi dengan memutus rantai ketidakadilan.
Pada akhirnya, pembangunan sejati adalah yang menumbuhkan harapan, bukan yang memangkasnya. Negara hadir bukan untuk mengatur siapa yang boleh hidup dan beranak-pinak, melainkan memastikan setiap anak bangsa, tanpa memandang kelas sosial, punya kesempatan untuk bermimpi dan mengubah nasibnya. Sebab bangsa yang besar bukanlah bangsa dengan penduduk yang sedikit, tapi yang mampu memberdayakan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.