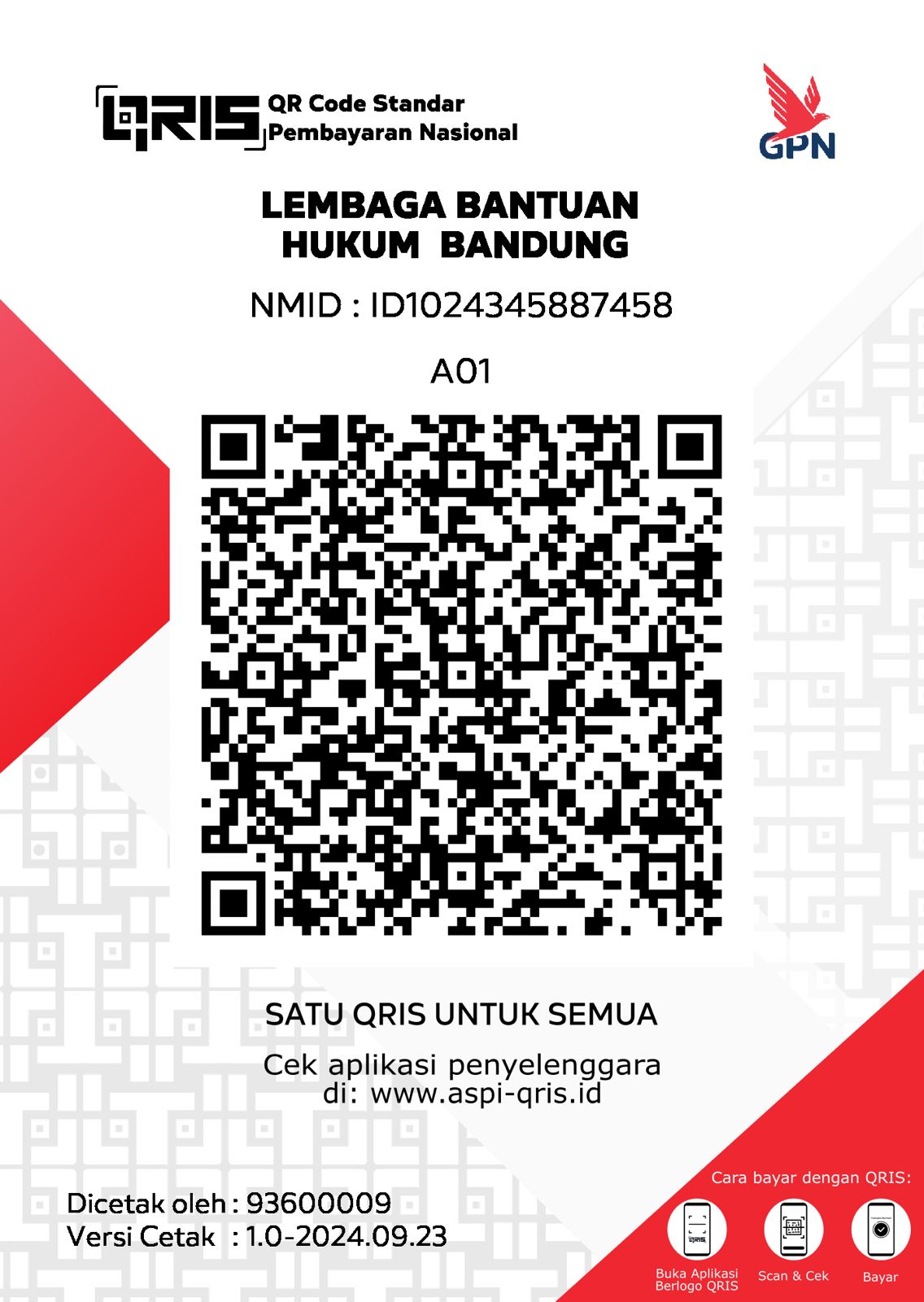PERNYATAAN SIKAP LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) BANDUNG DALAM MEMPERINGATI 24 SEPTEMBER SEBAGAI HARI BAGI PETANI DAN SELURUH BANGSA INDONESIA
“ ….. proyek-proyek IFIs, seperti Indonesia-Land Administration Project, memakai paradigma “Land Market” ini, untuk mengubah pola pengadaan tanah dari pola intervensi Negara ke pola pasar tanah, dan hendak mengintegrasikan semakin banyak persil-persil tanah ke dalam pasar tanah “ [1]
Tanggal 24 September 1960, bukan hanya diperingati sebagai hari lahirnya Undang-undang pokok agraria (UUPA), tetapi lahirnya sebuah hukum yang menasbihkan dirinya pada semangat anti kolonialisme. UUPA lahir dari pergolakan sejarah yang memandang bahwa setiap manusia Indonesia tanpa kecuali, berhak atas tanah dan sumber kehidupan lainnya demi tujuan konstitusional yang mulia : SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT.
UUPA pada pembentukannya tidak hanya menghapus sifat dualistik antara hukum perdata barat dan hukum adat, tapi secara fundamental berupaya merubah tatanan penguasaan sumber daya era kolonial, ke penguasaan dan pengelolaan sumber daya oleh rakyat dan untuk rakyat sebagaimana Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menjaminnya. UUPA membawa semangat Reforma Agraria yang pada pokoknya haruslah menakankan dirinya pada perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang tidak berpihak pada kepentingan kolonial, dan juga haruslah menempa dirinya pada tujuan tujuan yang berkelanjutan yang diarahkan pada perlindungan ekologis demi kemanfaatan bersama rakyat Indonesia. Semangat anti kolonialisme itu berarti bahwa setiap usaha dan upaya serta kebijakan yang dilakukan Negara tidak boleh berakibat pada hilangnya hak-hak rakyat untuk mengelola sumber kehidupannya sekaligus haruslah memberi perlindungan pada ruang hidup rakyat.
Semangat anti kolonialisme itu juga yang kemudian diadaptasi sebagai Visi Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI ) dan 15 Kantor di seluruh wilayah Indonesia termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. Visi[2] tersebut pada pokoknya adalah terwujudnya suatu tatatan masyarakat yang dilandasi oleh hubungan sosial yang adil serta beradab secara demokratis. Tatanan ini harus pula memuat sebuah sistem ekonomi, politik, dan hukum yang memastikan setiap orang tanpa kecuali untuk dapat memperoleh keadilan dan terlibat dalam setiap proses yang mengiringinya.
LBH Bandung menilai bahwa soal-soal agraria haruslah dipahami bukan hanya sebagai urusan tanah semata. Agraria haruslah dipahami sebagai kedaulatan tertinggi bangsa Indonesia dalam mengurus ruang hidupnya. Agraria haruslah dimaknai sebagai sumber kehidupan baik yang ada di atas tanah, segala yang terkandung di dalamnya serta jaminan atas perlindungan dan keberlanjutannya demi generasi bangsa Indonesia di masa depan. Dan Negara berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak hak rakyat tanpa kecuali.
Kami memandang bahwa semenjak Pengurus Publik, Presiden Joko Widodo dan jajarannya menyertakan agenda Reforma Agraria[3] ke dalam beragam kebijakan Nasionalnya, salah satunya ke dalam RPJMN mendapatkan respon yang beragam. Publik dan berbagai organisasi sipil mengapresiasi dan berharap bahwa kebijakan tersebut dapatlah dikatakan sebagai kebijakan yang pro terhadap kepentingan rakyat Indonesia, terutama petani. Akan tetapi pada kenyataannya, LBH Bandung menilai Presiden Joko Widodo beserta jajarannya secara sistematis dan massif telah melakukan pengingkaran terhadap hak hak rakyat di berbagai ruang ruang hidup dengan menerbitkan banyak sekali Peraturan perundang-undangan[4] yang di desain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui serangkaian aksi kebijakan yang berdampak pada tercerabutnya hak hak rakyat untuk mengelola sumber kehidupan dan melindungi ruang hidupnya sendiri. Kebijakan tersebut bahkan telah mengusir banyak rakyat di atas ruang hidupnya dengan bebagai dalih kepentingan umum yang tersemat padanya kepentingan korporasi besar baik swasta maupun BUMN.
Perampasan tanah dengan dalih kepentingan umum pembangunan infrastruktur di Jatigede dan Majalengka[5] telah berakibat pada hilangnya mata pencaharian ribuan petani yang menggantukan hidupnya dan keturunan pada sumber sumber pertanian. Di Indramayu dan Cirebon[6], atas nama energi yang semestinya surplus, ratusan hektar garapan warga yang menjadi sumber pemasukan keluarga petani dan nelayan harus rela terusir secara perlahan. Dan di Sukabumi butuh waktu tahunan untuk warga mendapat informasi atas pembangunan pabrik semen[7] yang kotor yang telah berjalan bertahun tahun lamanya, walaupun itu adalah bagian dari hak nya. Di Bandung warga Taman sari terintimidasi tiap hari nya oleh ancaman penggusuran yang dilakukan oleh perangkat Negara.
Catatan krisis lain juga ditunjukan oleh data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA). Sepanjang 2014, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 472 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan luasan mencapai 2.860.977,07 hektar. Konflik ini melibatkan sedikitnya 105.887 kepala keluarga (KK). Seiring dengan meluasnya proyek Master- plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, konflik agraria tertinggi pada tahun ini dapat dilihat terjadi pada proyek- proyek infrastruktur. KPA mencatat sedikitnya tel- ah terjadi 215 konflik agraria (45,55%) di sektor ini. Selanjutnya ekspansi perluasan perkebunan menempati posisi kedua yaitu 185 konflik agraria (39,19%), dilanjutkan oleh sektor kehutanan 27 (5,72%), pertanian20 (4,24%), pertambangan 14 (2,97%), perairan dan kelautan 4 (0,85%), lain-lain 7 konflik (1,48%). Diband- ingkan dengan 2013 terjadi peningkatan jumlah konflik sebanyak 103 atau meningkat 27,9% dari tahun lalu. Melihat banyaknya konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur sepanjang 2014, maka dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan turunannya adalah biang keladi mudahnya perampasan tanah rakyat atas nama pembangunan. Faktor genting lainnya, berjalannya program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang membagi tanah-air Indonesia dalam enam koridor ekonomi berbasiskan komoditas utama yang satu sama lain saling terhubung (konektivitas ekonomi) melalui pengembangan bisnis-bisnis ekploitasi dan ekplorasi sumber daya alam dalam skala luas. Sejalan dengan ekspansi pengerukan kekayaan alam itu, maka pembangunan infrastruktur pun semakin diperluas demi memperlancar bisnis-bisnis pengerukan SDA tersebut. Jika dilihat dari catatan KPA selama sepuluh tahun terakhir, maka sejak 2004 hingga ujung 2014 telah terjadi 1.520 konflik agraria dengan luasan areal konflik seluas 6.541.951.00 hektar, yang melibatkan 977.103 KK. Dengan demikian, rata-rata hampir dua hari sekali terjadi konflik agraria. Dalam satu hari, ada 1.792 hektar tanah rakyat yang dirampas hak penguasaan dan pengelolaanya, dan lebih dari 267 KK terampas tanahnya.[8]
Jumlah korban akibat konflik agrarian masih tinggi dari tahun ke tahun. Sepanjang 2014 korban te- was mencapai 19 orang, tertembak 17 orang, luka-luka akibat dianiaya 110 orang dan ditahan 256 orang. Tingginya angka korban jiwa, kekerasan dan krim- inalisasi atas rakyat dalam konflik agraria menunjukkan bahwa keterlibatan Polri/TNI dalam penanganan konflik agraria selama ini terbukti telah gagal memberikan rasa aman dan menjamin hak hidup rakyat dalam mempertahankan tanah airnya. Justru keterlibatan Polri/TNI mem- perparah aksi-aksi intimidasi dan teror terhadap warga. Selama melakukan pendampingan dan advokasi konflik agraria, utamanya yang dihadapi oleh basis-basis anggota KPA (serikat tani, organisasi masyarakat adat dan kelompok masyarakat miskin kota), KPA juga mendata ada 263 korban kriminalisasi aparat akibat konflik agraria. Kor- ban kriminalisasi konflik agraria dari Jawa Barat sebanyak 131 orang, Kalimantan Tengah 44 orang, Sumatera Utara 17 orang, Sulawesi Tengah 15 orang, Sumatera Selatan 14 orang, Jawa Tengah 13 orang, NTT 11 orang, Jawa Timur 8 orang, Bengkulu 4, Banten 3 orang, Kalimantan Barat 2 orang dan Kalimantan Timur 1 orang.[9]
Tentang Jumlah Konflik Agraria pada tahun 2016, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jika di tahun sebelumnya tercatat 252 konflik agraria, maka terdapat peningkatan signifikan di tahun ini, hampir dua kali lipat angkanya. Jika di rata-rata, maka setiap hari terjadi satu konflik agraria dan 7.756 hektar lahan terlibat dalam konflik. Dengan kata lain, masyarakat harus kehilangan sekitar sembilan belas kali luas provinsi DKI Jakarta. Perkebunan masih tetap menjadi sektor penyebab tertinggi konflik agraria dengan angka 163 konflik (36,22 %), disusul sektor properti dengan jumlah konflik 117 (26,00 %), lalu di sektor infrastruktur dengan jumlah konflik 100 (22,22 %). Kemudian, di sektor kehutanan sebanyak 25 konflik (5,56 %), sektor tambang 21 (4,67 %), sektor pesisir dan kelautan dengan 10 konflik (2,22 %), dan terakhir sektor migas dan pertanian yang sama-sama menyumbangkan sebanyak 7 konflik (1,56 %). Kembalinya sektor perkebunan sebagai penyumbang terbesar konflik agraria, menunjukkan bahwa perluasan lahan dan operasi perkebunan skala besar masih menjadi ancaman serius bagi gerakan pembaruan agraria di tanah air. Salah satu komoditas yang patut mendapatkan perhatian adalah ekpansi perkebunan sawit yang telah banyak melahirkan konflik agraria di beberapa wilayah di tanah air. Moratorium sawit yang juga diberlakukan di era Jokowi-JK tak mampu membendung ekspansi. Tercatat, menurut data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, setiap tahun, angka penguasaan tanah bagi perkebunan kelapa sawit terus merangkak naik. Dalam 5 tahun terakhir saja, telah bertambah 3 juta hektar luas lahan perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain, petani-petani menghadapi kesulitan karena tidak berpihaknya regulasi perkebunan. Mulai dari persoalan kemitraan yang tidak berkeadilan, penentuan sepihak atas harga, hingga kriminalisasi. Sementara itu, RUU Perkelapasawitan yang sedang bergulir di parlemen banyak mengartikulasi kepentingan korporasi, bukan petani. Beberapa pasal mendorong adanya kemudahan usaha perkebunan, serta mengatur dukungan pemerintah untuk usaha perkebunan, tetapi minim mendorong kemandirian petani dan penguatan koperasi sebagai bentuk usaha bersama secara kolektif. Sektor properti menduduki urutan kedua dari konflik agraria menyusul pengarusutamaan infrastruktur oleh Pemerintah, yang mana semakin mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli. Kondisi demikian secara tak langsung mendongkrak bisnis di sektor properti. Tapi sayangnya, pertumbuhan di sektor properti juga linear dengan tingginya angka konflik, karena praktiknya, pembangunan properti merampas tanah dan ruang hidup masyarakat. Tengok saja, pembangunan real estate oleh PT. Pertiwi Lestari (Salim Group) di Teluk Jambe, Karawang telah merampas tanah seluas 791 hektar, termasuk didalamnya tanah-tanah produktif penghasil pangan. [10]
Dari data di atas, LBH Bandung menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan Jokowi telah berdampak secara serius terhadap kerusakan ekologis, kerusakan lingkungan dan terusirnya rakyat dari ruang hidupnya. Ini kemudian yang kami sebut sebagai KOLONIALISME. Negara telah mengabdikan dirinya pada kepentingan kepentingan segelintir kelompok oligarki, kelompok korporasi tanpa sedikitpun mengindahkan hak hak rakyat.
Gelaran Global Land Forum (GLF) yang diadakan di Bandung tidak serta merta membawa konflik yang terjadi hari ini pada situasi yang lebih baik. Hal ini dikarenakan di beberapa peristiwa yang tercatat dan ditangani oleh LBH Bandung pada tahun 2016[11] dan 2017[12], Negara bukan hanya absen dalam melakukan perlindungan atas hak rakyat bahkan Negara menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang dominan.
Oleh karena hal hal di atas, LBH Bandung kemudian menyatakan sikap sebagai berikut:
- Menolak bentuk kolonialisme Negara melalui seperangkat peraturan perundang-undangan yang di desain untuk kepentingan korporasi, dan berdampak pada tercerabutnya hak hak rakyat
- Menolak intervensi asing dalam pengelolaan ruang hidup rakyat melalui skema hutang, baik langsung melalui Group Bank Dunia maupun perwakilannya seperti IFAD
- Menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat lokal yang sedang berjuang mempertahankan tanahnya
- Menolak segala bentuk represifitas aparat dalam penyelesaian konflik agraria
Narahubung:
Willy Hanafi: 081283000212
Syahri Dalimunthe: 082214462369
Gugun Kurniawan: 081322052016
[1] Noer Fauzi Rachman, BERSAKSI UNTUK PEMBAHARUAN AGRARIA : dari tuntutan lokal hingga kecendrungan global, Yogyakarta, INSIST PRESS, 2003, hal 94
[2] Visi YLBHI dan 15 LBH Kantor : Terwujudnya suatu suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (A just, humane and democratic socio-legal system); Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosudur-prosudur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (A fair and transparent institutionalized legal-administrative system); Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (An open political-economic system with a culture that fully respects human rights).
[3] Kebijakan yang dimaksud adalah Kebijakan Tanah Objek Reform Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial
[4] Lihat Perpres 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional beserta perubahannya di mana tidak ada satupun dasar argumentasi yang menyatakan kenapa proyek satu dan lainnya disebut sebagai strategis Nasional. Lihat Perpres 4 Tahun 2016 dan perubahannya di mana di dalamnya terdapa skema jual beli listrik di mana hal tersebut merupakan hal yang dilarang karena telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai perbuatan hukum yang inkonstusional. Lihat juga inpres 1 Tahun 2016 dan PP Tata Ruang no 13 Tahun 2017, terutama pada Pasal 114 a yang pada pokoknya menyatakan bahwa soal tata ruang dapat dipercepat melalui rekomendasi Menteri yang pada dasarnya, kemudian merubah tatanan ruang menjadi sesuatu yang tidak bernilai strategis bagi kepentingan lingkungan hidup.
[5] Lihat laporan Akhir tahun LBH Bandung 2016 Tentang Kasus Bandara Kertajati.
[6] Di Indramayu dan di Cirebon LBH Bandung melakukan gugatas atas Pembangunan PLT batu bara.
[7] Upaya warga Sinaresmi untuk mendapatkan Informasi IMB dan dokumen lingkungan lainnya harus sampai mekanisme hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.
[8] Lihat Laporan KPA 2014, Halaman 10-12
[9] Lihat lagi Laporan KPA 2014, Hal 14-15
[10] Lihat Laporan KPA Tahun 2016
[11] 59 kasus ditangani LBH Bandung salah satunya terkait isu pembangunan infrastruktur, tanah, serta lingkungan
[12] 132 laporan masuk terkait krisis ruang hidup baik di perkotaan dan pedesaan.