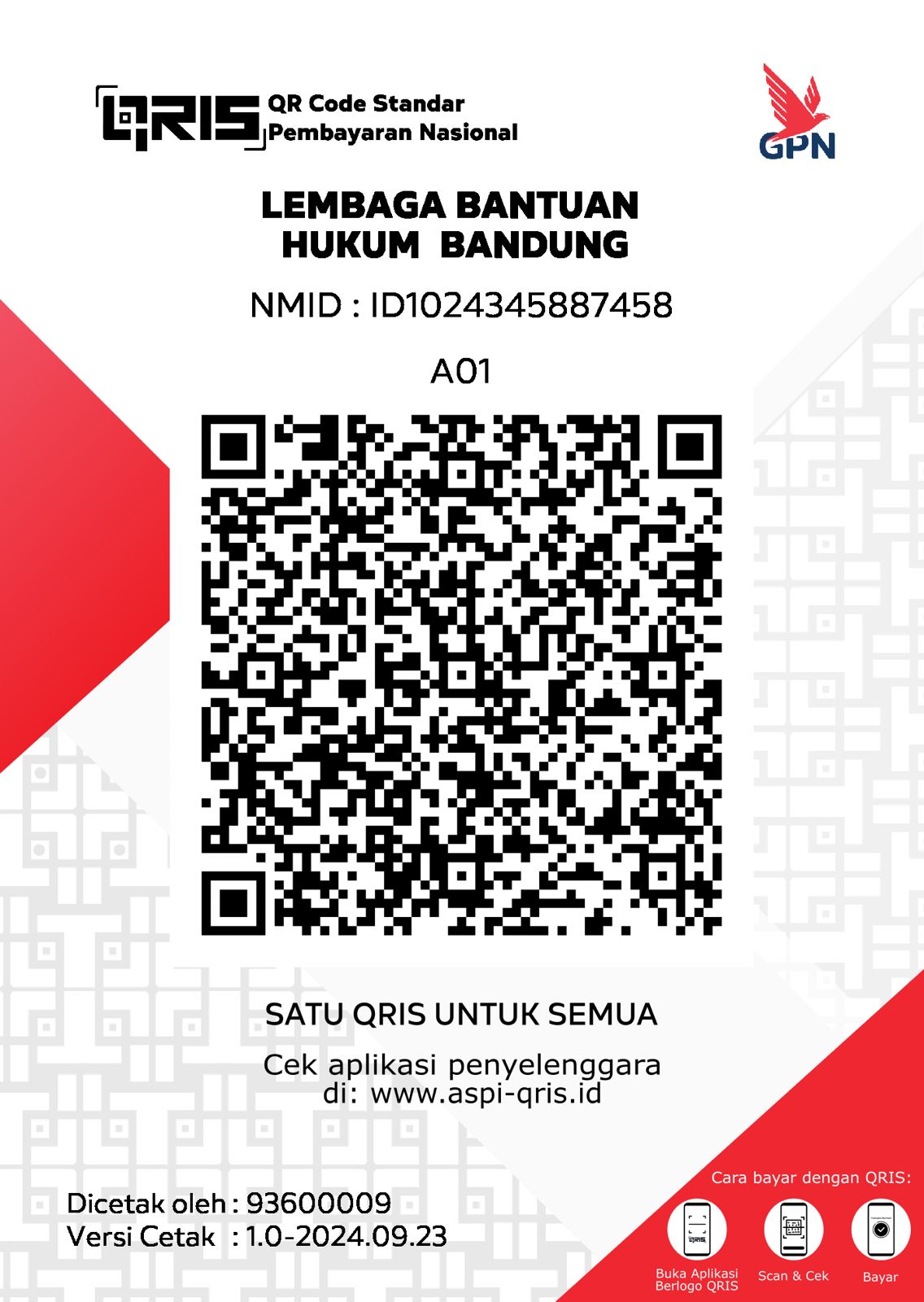OTONOMI KHUSUS PAPUA: DESENTRALISASI ASIMETRIS ATAU GERRYMANDERING PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024?
Oleh: Adhitiya Augusta Triputra
Pada tahun 2022 terdapat 4 wilayah di Papua mendapatkan pemekaran wilayah dengan otonomi khusus lewat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua sebagai dasar dibentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Dasar hukum pemekaran wilayah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
Sejatinya pemekaran wilayah yaitu untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam arti yang sebenarnya pemekaran harus memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat. Pemekaran haruslah menjadi aspirasi bersama yang jauh dari kepentingan segilintir kelompok dan elite politik. Yang menjadi pertanyaan apakah pemekaran daerah otonomi baru tersebut memang bottom-up atau top-down? Secara konsep wilayah tersebut merupakan desentralisasi asimetris.
Ahli pertama yang memulai debat seputar desentralisasi asimetris adalah Charles Tarlton (1965) dari University of California, USA. Menurut ilmuwan ini, pembeda inti antara desentralisasi biasa (simetris) dan desentralisasi asimetris terletak pada tingkat kesesuaian (conformity) dan keumuman (commonality) dalam hubungan suatu level pemerintahan (negara bagian/daerah) dengan sistem politik, dengan pemerintah pusat maupun antar negara bagian/daerah. Pola simetris ditandai oleh “the level of conformity and commonality in the relations of each separate political unit of the system to both the system as a whole and to the other component units”. Di sini, hubungan simetris antar setiap unit lokal dengan pemerintah pusat tersebut didasari jumlah dan bobot kewenangan yang sama.
Sementara dalam pola asimetris, satu atau lebih unit politik atau pemerintahan lokal “posesed of varying degrees of autonomy and power”. Berbedanya derajat otonomi dan kekuasaan berupa ketidak–seragaman pengaturan muatan kewenangan itu membentuk derajat hubungan yang berbeda pula antar negara bagian/daerah asimetris dengan unit-unit politik lainnya, baik secara horisontal (antar daerah) maupun vertikal (dengan pusat). Khusus mengenai pola asimetris, Tarlton menekankan: “In the model asymmetrical system each component unit would have about it a unique feature or set of features which would separate in important ways, its interests from those of any other state or the system considered as a whole”.
Dalam hal bentuk negara, walau pada awalnya Tarlton menulis tema asimetri dalam kerangka negara federal, perkembangan di kemudian hari menunjukan bahwa konsep dan penerapan kebijakan atas model tersebut mulai diadopsi di negara-negara kesatuan, berupa special autonomy, special territory, atau yang di Indonesia dikenal sebagai otonomi khusus, daerah khusus dan daerah istimewa‘. Untuk mempertegas hal itu, Gabriele Ferrazzi (2008) dari University of Guelph, Canada, menulis: “asymmetric decentralization (AD) is common throughout the world, in both unitary and federal countries”. Salah satu manifetasinya adalah melalui pemberian status otonomi khusus untuk satu atau lebih unit lokal.
Menurut Robert Endi Jaweng (2011) dan sejalan dengan kategori Richard Bird (2003) Keberfungsian/kemanfaatan model asimetri sekiranya akan menjadi lebih terukur dalam penilaiannya jika kita membedakan antara jenis asimetri itu sendiri, terutama yang berjenis asimetri politik (political asymmetry) dan asimetri administratif (administrative asymmetry). Jika pertimbangannya adalah politik maka desentralisasi asimetris yang terbentuk berjenis political asymmetry, sementara pilihan asimetri yang berbasis pertimbangan efisensi atau pembangunan kapasitas pemerintahan mendorong lahirnya kategori kedua, yakni jenis administrative asymmetry.
Dalam pemekaran Papua, terdapat permasalahan yang patut dipertanyakan yaitu terkait UU Otsus Papua pada Pasal 76 ayat (3) yang menyatakan bahwa “pemekaran daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah”. Jika merujuk UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait masa persiapan yang mengatur bahwa untuk memekarkan satu daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus melewati tahapan daerah persiapan selama 3 tahun. Selain tidak ditemukan alasan penting mengapa pemerintah memutuskan untuk mengenyampingkan masa persiapan bagi pemekaran Papua, tetapi juga pemekaran Papua minim pelibatan rakyat Papua dan kurang memenuhi aspek pengkajian mendalam yang dilakukan.
Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa semua hal itu dilakukan secara terburu-buru, dilakukan dengan fast-track legislation, dan disahkan di tahun 2022 yang dimana pada tahun 2024 terdapat perhelatan pemilu serentak. Kebijakan pemekaran daerah papua ini sangat didominasi oleh kepentingan politik dengan adanya desentralisasi mendorong lahirnya praktik dinasti politik. Di mana elite politik yang memiliki modal sosial, ekonomi, politik, dan sosial budaya cenderung mengendalikan kekuasaan di tingkat lokal. Dalam konteks pusat dan daerah, pemekaran adalah upaya para elite politik lokal untuk merebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan yang ada pada pemerintahan pusat, sehingga kesan dari pemekaran hanyalah arena kekuasaan semata.
Berkenaan dengan itu, jika kita lihat ketentuan Pasal 6A ayat 3 UUD 1945, syarat terpilihnya seorang menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia adalah memperoleh suara lebih dari 50% dengan sebaran sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Ketentuan ini berarti mensyaratkan perolehan suara mayoritas dan persebaran suara di setiap provinsi. Dapat dipahami bahwa kontruksi hukum yang dibangun didasarkan pada sebaran jumlah penduduk yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dilihat dari bunyi norma hukumnya, pasal tersebut sama sekali tidak menyebutkan terkait keberlukan dalam jumlah calon yang dipilih yang pada akhirnya putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang pilpres hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sederhananya, dalam hal dua pasangan calon maka pemilihan sudah pasti dilakukan dalam satu kali putaran (suara mayoritas), tidak perlu dilakukan adanya putaran kedua (sebaran suara).
Pada Pilpres 2024 kita ketahui jika pasangan calon berjumlah tiga yaitu Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud yang berarti diperlukannya 2 putaran jika syarat sebaran suara provinsi tidak dipenuhi. Hal inilah yang menjadi potensi jika Pemekaran 4 wilayah Papua sangatlah berpotensi terjadinya Gerrymandering karena hasil pemekaran ini adalah kebijakan dari pemerintah sebelumnya dengan kepentingan politik untuk memenangkan salah satu calon dengan tujuan untuk menghindari terjadinya dua putaran atau memastikan memperbesar peluang kejadian untuk memenangkan pemilihan dengan satu putaran. Gerrymandering adalah tipu daya yang diciptakan oleh Elbridge Gerry, Gubernur Massachusset tahun 1815 yang pada akhirnya menjadi wakil presiden AS dengan menetapkan perbatasan daerah pemilihan dicampur aduk untuk menggembosi 6 partai politik di perkotaan dalam rangka menguntungkan pihaknya.
Untuk menghitung bagaimana potensi gerrymandering ini menunjukan terjadinya penggembosan suara bagi calon lain maka untuk menghitungnya dapat menggunakan distribusi binomial, dimana peluang satu pasangan calon dari tiga pasangan untuk memenuhi syarat sebaran suara (≥20% suara di ≥20 dari 38 provinsi) Dengan asumsi distribusi suara acak dan merata antar 3 pasangan (p = 1/3), hanya sekitar 1 dari 100 simulasi yang menghasilkan sebaran suara memenuhi syarat konstitusional ini. Artinya, sangat kecil kemungkinan pasangan calon bisa langsung menang dalam satu putaran jika suara benar-benar terbagi rata. Akan berbeda hasilnya jika dari 38 provinsi dengan 4 provinsi sudah “di tangan”, peluangnya melonjak hampir 6 kali lipat. Hitungan 38/2 adalah 19 yang berarti dengan hitungan minimum dibulatkan syarat minimal menjadi 20 provinsi. Logika strategisnya jika 4 provinsi sudah sebagai “modal awal” maka tinggal 16 provinsi menjadi target utama minimum untuk memenangkan pemilihan presiden dalam satu putaran. Ini menjadi tantangan berat bagi lawan calon lainnya yang dimana akan sulit untuk mendapat dukungan ke 20 provinsi dengan tanpa adanya “modal awal”.
Pemekaran Papua dengan diberikannya otonomi khusus yang dilakukan secara terburu-buru tanpa melakukan evaluasi secara mendalam terkait masa persiapan yang justru dihilangkan di dalam UU Otsus Papua yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Pemda yang menghendaki adanya masa persiapan dan hanya menjadi strategi politik untuk Pemilu 2024. Hal-hal seperti inilah yang justru melanjutkan kegagalan-kegagalan seperti Daerah Otonomi Baru lainnnya yang sudah terjadi, mayoritas kegagalan DOB disebabkan karena tidak adanya masa persiapan yang baik. DOB Papua justru berpotensi akan seperti DOB lainnya yang saat ini bertumpu kepada transfer keuangan dari pusat sehingga mempersulit DOB dalam mewujudkan desentralisasi fiskalnya.
Dalam pandangan lain, pola-pola seperti ini yang justru menjadi alat oleh pusat untuk tetap mencengkram kekuasaannya di Papua dengan ketergantungan finansial, apalagi dengan pemberian desentralisasi asimetris (otonomi khusus) yang secara finansial mendapat dana alokasi khusus. Kekhawatiran lainnya selain dengan dihilangkannya masa persiapan adalah belum terselesaikannya konflik dan kekerasan di Papua. Pemekaran ini lebih bermuatan politis daripada murni berasal dari prakarsa rakyat Papua. Sehingga jika kita refleksikan setiap penerapan DOB lewat desentralisasi asimetri maupun simetri tidak pernah memiliki grand-design yang terukur dan akuntabel khususnya untuk wilayah Papua.
Daftar Pustaka:
Bird, Richard M. 2003. “Asymmetric Fiscal Decentralization: Glue or Solvent”, Working Paper 03-09, April, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.
Ferrazzri Gabriele. 2008. “Special Autonomy: A Common Form of Asymmetric Decentralization”, Paper for Aceh Workshop, November 19.
Endi Jaweng, Robert. 2011 Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia, CSIS, Vol 40 no 2 Juni 2011
Rini Maisari. 2022. Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua. Lex Renaissance No 4 Vol 7 Oktober 2022
Dafrin Muksin dkk. 2021. Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 2 2021.
Nes Tabuni dkk. 2023. Perpektif Pemerintah Provinsi Papua Pada Penerimaan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Papua. Agrisosioekonomi Volume 19 Nomor 2, Mei 2023